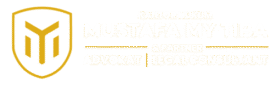Oleh : Mustafa MY Tiba, S.Pd.I, S.H
Oleh : Mustafa MY Tiba, S.Pd.I, S.H
Kasus Tom Lembong: Potret Hukum sebagai Alat Kekuasaan
Kasus Tom Lembong menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai korban kekuasaan. Diduga, perbedaan pandangan dan afiliasi politik menjadikannya target kriminalisasi dengan dalih hukum. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Dalam situasi seperti ini, hukum kehilangan substansinya sebagai instrumen keadilan, dan justru menjadi alat represi terhadap lawan politik. Penegakan hukum berubah menjadi proyek politik, bukan amanah konstitusional.
Pendahuluan
Penegakan hukum seharusnya menjadi wujud dari cita-cita keadilan dalam sebuah negara hukum. Namun dalam praktiknya, hukum sering kali tidak berdiri sendiri sebagai penjaga nilai, melainkan digunakan sebagai alat kekuasaan. Fenomena ini menjadikan hukum ambigu: apakah hukum ditegakkan demi keadilan, atau hanya digunakan demi kepentingan tertentu?
Menegakkan Hukum vs Menggunakan Hukum
Menegakkan hukum berarti mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, menggunakan hukum tidak selalu bertujuan demikian. Dalam banyak kasus, hukum justru dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan yang menyimpang, diskriminatif, bahkan represif.
Kolaborasi antara keahlian hukum, kekuasaan politik, dan kepentingan ekonomi dapat mengubah wajah hukum menjadi alat pembenar kekerasan struktural. Dalam konteks ini, korupsi, pelanggaran HAM, serta diskriminasi sistematis dapat dilakukan dengan “berlandaskan hukum”, hingga nyaris tidak terlacak.
Dalam teori dan idealisme negara hukum, menegakkan hukum merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Ia menuntut kejujuran intelektual dan integritas moral dari aparat penegak hukum untuk menjadikan hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan prosedur formal.
Sebaliknya, menggunakan hukum berarti memperlakukan hukum sebagai alat atau instrumen demi mencapai tujuan tertentu—yang bisa saja tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Dalam praktiknya, menggunakan hukum sering kali tidak didasarkan pada niat untuk menegakkan nilai-nilai luhur, tetapi untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang pada hakikatnya menyimpang, termasuk represi politik, diskriminasi sosial, dan penyelewengan kekuasaan.
Paradoks Hukum: Alat Keadilan atau Alat Kekuasaan?
Perbedaan antara menegakkan dan menggunakan hukum sering kali tidak kasat mata, sebab keduanya memakai perangkat dan simbol yang sama: undang-undang, pengadilan, jaksa, polisi, dan hakim. Namun, bedanya terletak pada niat dan arah. Bila hukum ditegakkan untuk semua tanpa kecuali, maka hasilnya adalah keadilan. Tapi bila hukum digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok atau elite tertentu, hasilnya adalah ketidakadilan yang terselubung.
Misalnya:
- Seorang aktivis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah bisa dikenai pasal karet “penyebaran hoaks” atau “mengganggu ketertiban umum”, sementara politisi pendukung penguasa bebas menyebarkan ujaran kebencian tanpa proses hukum.
- Seorang pengusaha kecil dijerat pidana karena pelanggaran administratif, sedangkan korporasi besar yang merusak lingkungan dibiarkan bebas karena dekat dengan kekuasaan.
Kolaborasi Tiga Unsur: Hukum, Kekuasaan, dan Oligarki
Yang menjadikan penggunaan hukum sangat berbahaya adalah ketika ia menjadi hasil kolaborasi antara:
- Keahlian hukum (yang memahami celah dan ruang abu-abu hukum),
- Kekuasaan politik (yang memiliki kewenangan koersif), dan
- Kepentingan ekonomi ologarki (yang mencari legitimasi untuk akumulasi kekayaan).
Dalam konfigurasi ini, hukum berubah fungsi: dari penjaga keadilan menjadi alat justifikasi struktural. Praktik korupsi yudisial, misalnya, bukan hanya menyimpangkan hukum, tetapi menggunakan hukum itu sendiri untuk menutupi penyimpangan, seperti putusan “bersih” atas kasus padahal sarat suap dan manipulasi. Maka tak heran jika korupsi di lembaga peradilan sering kali sangat sulit dilacak karena semuanya “terlihat sah”.
Implikasi Sosial dan Demokrasi
Penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan memiliki implikasi luas:
- Ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara.
- Normalisasi ketidakadilan, di mana masyarakat menerima bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
- Pembungkaman suara kritis, di mana hukum dijadikan alat untuk merepresi oposisi politik, aktivis, jurnalis, bahkan akademisi.
Dengan demikian, yang menjadi masalah bukan hanya soal hukum yang digunakan secara salah, tetapi budaya kekuasaan yang menganggap hukum sebagai milik dan alat mereka. Padahal dalam demokrasi dan negara hukum sejati, hukum adalah milik rakyat, dan ditegakkan untuk rakyat.
Hukum dan Budaya Penguasa
Dalam sistem pemerintahan yang semakin totaliter, hukum kerap diagung-agungkan di tataran wacana, namun pada kenyataannya hanya digunakan sebagai simbol legitimasi kekuasaan. Penegakan hukum menjadi semu, dan diskriminasi justru dilembagakan. Hukum tak lagi untuk semua, melainkan untuk siapa yang berkuasa.
Rezim otoriter bahkan memanfaatkan hukum sebagai dalih untuk melakukan kejahatan serius, termasuk pelanggaran HAM berat. Dengan keyakinan bahwa tindakannya sah menurut hukum yang dibuat atau dikendalikan sendiri, pelaku tak lagi merasa bersalah. Hukum berubah menjadi tameng yang membenarkan kejahatan.
Ketika Keadilan Menjadi Korban Kekuasaan
- Hukum Sebagai Wacana, Bukan Realitas
Dalam rezim yang cenderung otoriter, hukum tidak lagi menjadi mekanisme keadilan universal, melainkan dijadikan alat retoris: dibicarakan, dipajang, bahkan dijadikan simbol integritas—namun tidak pernah benar-benar ditegakkan secara adil.
- Pemerintah kerap menggunakan istilah “penegakan hukum” untuk membungkam kritik, bukan untuk menyelesaikan pelanggaran nyata.
- Undang-undang dibentuk atau dimodifikasi bukan untuk melindungi warga negara, melainkan untuk melanggengkan kekuasaan dan mengamankan kepentingan elite.
- Simbol hukum (palu sidang, toga hakim, polisi berseragam) dijadikan alat propaganda seolah negara berjalan sesuai prinsip hukum, padahal kenyataannya hukum telah dijarah maknanya.
- Budaya Kekuasaan: Menciptakan Hukum untuk Mengunci Oposisi
Penguasa yang sudah kehilangan legitimasi publik sering kali beralih pada hukum sebagai alat represi legal. Di sini budaya kekuasaan berkembang menjadi brutal:
- Pembentukan hukum yang represif: munculnya undang-undang kontroversial seperti pasal karet (misal: penghinaan terhadap penguasa, ujaran kebencian, penyebaran hoaks), yang digunakan untuk mengkriminalisasi kritik dan membatasi kebebasan berpendapat.
- Penegakan hukum secara selektif: orang-orang dekat penguasa atau berasal dari kelompok dominan mendapat kekebalan, sementara oposisi politik, aktivis, atau minoritas ditindak tegas, seringkali tanpa proses hukum yang fair.
- Peradilan sebagai alat kekuasaan: hakim dan jaksa tidak lagi independen, tapi justru tunduk pada tekanan politik. Putusan-putusan dijadikan “panggung politik” untuk membenarkan tindakan penguasa.
- Hukum sebagai Tameng Kejahatan
Dalam kondisi ini, hukum tidak hanya gagal melindungi keadilan—ia berubah menjadi pelindung kejahatan.
- Pelanggaran HAM berat seperti penghilangan orang, pembantaian, penyiksaan, dan pembatasan akses informasi bisa terjadi dengan dalih “mengamankan negara”, “membela kedaulatan”, atau “memerangi terorisme”.
- Pelaku merasa tidak bersalah karena tindakan mereka disahkan oleh peraturan hukum atau didukung oleh aparat penegak hukum yang sudah disetir.
- Dalam beberapa kasus, kejahatan negara menjadi sulit diusut secara hukum, karena semua prosedurnya tampak legal: surat penangkapan ada, proses pengadilan berlangsung, dan aparatnya memakai atribut hukum.
- Normalisasi Kekerasan Legal
Kebrutalan hukum yang dilakukan oleh rezim otoriter tidak hanya terlihat dalam tindakan fisik, tapi juga dalam proses normalisasi kekerasan legal, yaitu:
- Mendefinisikan ulang kejahatan dan musuh negara: rakyat yang memprotes dianggap makar, jurnalis investigatif dianggap penyebar kebencian, mahasiswa dituding anarkis.
- Menghapus rasa bersalah kolektif: karena tindakan yang brutal dilakukan dengan dasar hukum, masyarakat dipaksa untuk percaya bahwa semua itu sah—dan korban dijustifikasi sebagai “mengganggu stabilitas”.
- Akibatnya, masyarakat mati rasa terhadap ketidakadilan, karena hukum yang semestinya menjadi harapan terakhir justru menjadi sumber ketakutan.
- Contoh Nyata:
- Apartheid Afrika Selatan: sistem hukum rasialistik disusun rapi agar diskriminasi terhadap warga kulit hitam dianggap legal.
- Rezim Nazi Jerman: hukum digunakan untuk mengabsahkan pembantaian orang Yahudi dan minoritas lain.
- Orde Baru di Indonesia: penggunaan UU Subversif dan Perpu untuk memberangus lawan politik dan aktivis pro-demokrasi, termasuk pembungkaman media dan pembenaran kekerasan militer.
Ketika hukum dikendalikan oleh budaya penguasa yang brutal, maka keadilan menjadi korban pertama. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi melindungi yang lemah, tapi justru mengukuhkan dominasi yang kuat. Hukum tidak lagi netral, melainkan berpihak pada siapa yang memiliki kuasa untuk menafsirkan dan menggunakannya.
Hukum Internasional dan Hegemoni Global
Fenomena “penggunaan hukum” tak hanya terjadi di tingkat domestik, tapi juga dalam pergaulan antarbangsa. Amerika Serikat, misalnya, kerap dituding memperkosa hukum internasional demi kepentingan geopolitik dan hegemoninya. Dalih “perang melawan terorisme” telah digunakan untuk menginvasi Afghanistan dan Irak, meski tindakan tersebut menimbulkan penderitaan massal dan kehancuran.
Logika serupa juga digunakan Israel dalam agresinya terhadap Palestina dan Lebanon. Dengan mengklaim “membela diri”—sebuah dalih yang dibenarkan hukum internasional—Israel melakukan pembantaian yang nyata-nyata merupakan pelanggaran HAM berat. Di sinilah hukum berubah menjadi alat pembenar, bukan alat pelindung.
Hukum dalam Perdagangan Global
Dalam konteks hukum perdata internasional seperti hak kekayaan intelektual (HKI), negara maju memanfaatkan sistem hukum global untuk mempertahankan dominasi ekonomi mereka. Negara-negara berkembang didorong untuk “taat hukum” terhadap sistem yang sesungguhnya menciptakan ketergantungan struktural. Akibatnya, semakin patuh negara miskin terhadap hukum internasional, semakin jauh mereka dari kemandirian.
Paradoks Profesi Hukum: Antara Menegakkan dan Menggunakan Hukum
Polisi, jaksa, hakim, advokat, politisi, hingga birokrat hukum hidup dalam paradoks antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum. Menegakkan hukum tanpa prosedur hukum berisiko melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, menggunakan hukum tanpa niat menegakkan keadilan justru menciptakan ketidakadilan yang sistematis.
Profesi-profesi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, birokrat, dan politisi sesungguhnya berdiri di tengah dua kutub yang saling tarik-menarik:
- Menegakkan hukum: artinya berkomitmen pada keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
- Menggunakan hukum: artinya memperlakukan hukum sebagai alat formal yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan, baik tujuan etis maupun manipulatif (termasuk melindungi kepentingan pribadi, kelompok, atau kekuasaan).
Paradoksnya muncul ketika:
- Menegakkan hukum tanpa prosedur hukum (misalnya demi “rasa keadilan” atau ketertiban) justru berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Contoh: main hakim sendiri oleh aparat, razia tanpa dasar hukum, penggerebekan ilegal, dll.
- Menggunakan hukum secara prosedural tapi tanpa niat menegakkan keadilan, hanya sekadar menjalankan rutinitas atau melayani kekuasaan, justru menjadi bentuk kejahatan legal. Contoh: vonis “bebas” atas pelaku korupsi karena teknikalitas, kriminalisasi aktivis dengan pasal karet, atau SP3 atas kasus besar karena tekanan politik.
Contoh Nyata dari Paradoks Ini:
- Polisi yang berkata “kami hanya menjalankan perintah” padahal perintah itu melanggar hukum.
- Jaksa yang menuntut berdasarkan tekanan politik, bukan berdasar alat bukti.
- Hakim yang memutus perkara dengan pertimbangan non-yuridis (misalnya demi menjaga stabilitas politik).
- Advokat yang menyalahgunakan profesinya bukan untuk membela hukum, tetapi untuk meloloskan kejahatan melalui celah hukum.
- Politisi yang membuat undang-undang bukan untuk kemaslahatan umum, tapi demi mempersempit ruang oposisi atau memperkuat dominasi ekonomi kelompoknya.
Fenomena dan Ciri-Ciri Negara Menuju Kehancuran Akibat Penyimpangan Hukum
Ketika paradoks profesi hukum ini tidak disadari, tidak diperbaiki, atau justru dilembagakan, maka itu menjadi pertanda bahwa suatu negara sedang menuju kehancuran, baik secara hukum, moral, maupun politik. Berikut ciri-cirinya:
- Hukum Tidak Lagi Netral
Indikasi: Lembaga hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
- Pelanggaran hukum oleh rakyat kecil ditindak tegas.
- Korupsi pejabat dibiarkan atau dilindungi.
- Penegakan hukum menjadi alat balas dendam politik.
- Independensi Peradilan Hilang
Indikasi: Hakim tunduk pada tekanan politik atau ekonomi.
- Putusan pengadilan dapat “dipesan”.
- Proses peradilan tidak transparan.
- Lembaga seperti MA dan KY menjadi simbol semata.
- Kriminalisasi Oposisi dan Aktivis
Indikasi: Penggunaan pasal karet terhadap pengkritik pemerintah.
- Kritik dianggap makar atau hoaks.
- Ruang publik dikuasai propaganda negara.
- Aktivis dibungkam melalui proses hukum semu.
- Hukum Dijadikan Proyek Elite
Indikasi: Undang-undang dibentuk secara kilat, minim partisipasi.
- Legislasi disusun berdasarkan pesanan oligarki.
- Hukum ekonomi dan investasi hanya menguntungkan segelintir orang.
- Rakyat dijadikan objek, bukan subjek hukum.
- Aparat Hukum Menjadi Alat Represi
Indikasi: Polisi dan jaksa tidak lagi menjadi pelayan publik, tapi alat kekuasaan.
- Penanganan perkara sangat politis.
- Aparat digunakan untuk kepentingan partai atau elite tertentu.
- Tidak ada mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran aparat.
- Rakyat Kehilangan Kepercayaan terhadap Hukum
Indikasi: Munculnya perlawanan sipil, gerakan keadilan alternatif, vigilante.
- Masyarakat lebih percaya pada “pengadilan jalanan” daripada lembaga formal.
- Maraknya radikalisasi akibat ketidakadilan yang terus dibiarkan.
- Wibawa negara jatuh, baik di mata rakyat maupun internasional.
Akhirnya: Hancurnya Fondasi Bangsa
Ketika hukum diselewengkan, yang hancur bukan hanya sistem hukum, tetapi seluruh sendi kehidupan bernegara:
- Rakyat kehilangan rasa keadilan → timbul frustrasi sosial.
- Institusi hukum kehilangan martabat → legitimasi negara runtuh.
- Kekuasaan menjadi sewenang-wenang → muncul potensi konflik sipil.
Seperti dikatakan oleh Aristoteles:
“Keadilan adalah syarat utama kelangsungan sebuah negara. Tanpa keadilan, negara hanyalah kekuasaan yang menindas dengan nama hukum.”
Kasus Tom Lembong: Potret Hukum sebagai Alat Kekuasaan
Kasus Tom Lembong menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai korban kekuasaan. Diduga, perbedaan pandangan dan afiliasi politik menjadikannya target kriminalisasi dengan dalih hukum. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Dalam situasi seperti ini, hukum kehilangan substansinya sebagai instrumen keadilan, dan justru menjadi alat represi terhadap lawan politik. Penegakan hukum berubah menjadi proyek politik, bukan amanah konstitusional.
Kesimpulan
Hukum harusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan alat pembenar kejahatan. Ketika hukum digunakan hanya untuk memperkuat kekuasaan dan bukan untuk ditegakkan secara adil, maka kepercayaan publik akan hukum runtuh. Kita butuh keberanian untuk mengembalikan marwah hukum, agar ia benar-benar berdiri sebagai pelindung keadilan, bukan alat kejahatan
🎯 Siap Dibela?
Percayakan urusan hukum Anda kepada tim yang telah terbukti berpengalaman dan berhasil.
📞 Konsultasi Gratis | 📧 info@mustafamytiba.com | 📍 Kantor Hukum Mustafa MY Tiba & Partners